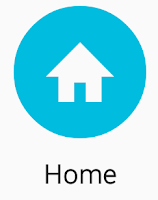Sang Pangeran Mesir itu, digumuli pertanyaan-pertanyaan dari dalam dirinya, kegelisahan pencarian kebenaran. Dan Allah menyiramnya dengan kebingungan yang lebih besar lagi.

Ia dipaksaNya menelan kenyataan bahwa ayahnya pernah membantai jutaan bayi lelaki Bani Israil. Ia dipaksaNya menelan kenyataan bahwa ayahnya menganggap Bani Israil adalah warga kelas dua yang rendah, bodoh, dan memang patut diperbudak. Puncaknya, ia dipaksaNya menelan kenyataan bahwa dirinya sendiri ternyata merupakan seorang anak Bani Israil, keturunan warga budak kelas dua, yang dipungut dari sungai Nil.
Pada saat ini, pada diri seorang Pangeran Musa lenyaplah sudah harga dirinya. Hancur semua masa lalunya. Dia hanyalah seorang tanpa sejarah sekarang. Ditambah lagi ia telah membunuh seorang lelaki, maka larilah ia terlunta-lunta, menggelandang di padang pasir, mempertanyakan siapa dirinya sebenarnya.
Justru, pada saat inilah ia berangkat dengan pertanyaan terpenting bagi seorang pejalan suluk, yang telah tumbuh disiram subur oleh Allah dengan air kegalauan: “Siapa diriku sebenarnya?”.
Dan kisah lanjutannya, di ujung padang pasir Madyan ada seorang pembimbing untuk menempuh jalan menuju Allah, yaitu Nabi Syu’aib, yang lalu menyuruh anaknya untuk menjemput Musa dan membawa Musa kepadanya.
Di bawah bimbingannya, Musa dididik menempuh jalan taubat, untuk “arif akan nafs (jiwa)-nya sendiri”. Dan dengan bimbingan Syu’aib akhirnya Musa mengerti dengan sebenar-benarnya, bahwa dirinya diciptakan Allah untuk menjadi seorang Rasul bagi bangsa Bani Israil, bukan sebagai seorang pangeran Mesir. Ia menemukan kembali misi hidupnya, tugas kelahirannya yang untuk apa Allah telah menciptakannya.
Akhirnya Musa menemukan jawaban, untuk apa dia diciptakan.